“Satu suapan lagi! Habis ini boleh tidur.” katanya sambil menyuapkan sesendok nasi ke dalam mulutku. Dengan malas kuturuti kata-kata itu, aku membuka mulut dan berjuang keras untuk melawan rasa mual di perutku, agar makanan yang telah kutelan tidak tumpah lagi. Ini suapan terakhir semoga tidak mengacaukan semuanya. Sambil mengunyah pelan-pelan, aku benahi selimut tidurku dan mencoba memejamkan mata. Rohmi beranjak pergi, mungkin ke dapur. Biasanya dia menghabiskan sisa makananku itu sebelum akhirnya menyusulku tidur.
Malam beranjak larut. Mataku terbuka kembali seketika Rohmi merebahkan tubuhnya di sebelahku. Sempat kulihat wajah letihnya yang menyiratkan perasaan pilu. Perempuan itu masih setia menemaniku hingga di usia senja seperti ini. Diapun mulai memejamkan mata. Aku sering memperhatikan raut wajahnya yang belakangan semakin menunjukkan penderitaan. Bukan lantaran merasakan penderitaan yang kualami, tetapi penderitaan yang lain. Entah karena apa. Aku tidak bertanya. Paling-paling dia tidak lagi mau bercerita. Alasannya sudah bisa ditebak: tidak mau menambah penderitaanku.
Perempuan itu tertidur semakin lelap. Wajahnya yang redup seperti rembulan, seakan menahan kepedihan hatinya. Rohmi… andaikan saja aku masih akan sehat seperti hari-hari lalu… niscaya aku akan lebih membahagiakanmu lagi. Kesetiaanmu begitu dalam, saat ini aku tak sanggup membalasnya dengan apapun. Sekarang aku lebih banyak membebaninya dengan sakitku. Tapi aku juga tidak pernah meminta sakit. Dia datang begitu saja tanpa permisi. Dokter bilang aku sudah stadium lanjut. Sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Aku hanya tinggal menunggu waktu dan keajaiban.
Oh, andaikan saja…. Seandainya… semakin banyak andai-andai dalam pikiranku belakangan ini. Salahku juga. Mengapa tidak saat masih sehat dulu aku sering menjaga diri. Belakangan sering muncul penyesalan. Penyesalan yang tidak berarti apa-apa. Penyesalan yang tiada berguna. Baru sekarang merasa kalau kesehatan itu begitu mahal. Sudah berapa juta uang habis buat perawatanku di Rumah Sakit, belum lagi buat ke sana ke mari. Penghasilan pun sudah tidak ada. Apa yang bisa dihasilkan dari si tua renta ini? Aku benar-benar bergantung kepada Rohmi. Hanya dia satu-satunya harta yang aku punya. Pun aku tak mau lagi semakin membebaninya. Lebih baik aku pulang paksa dari Rumah Sakit agar Rohmi bisa merawatku di rumah. Toh sudah tidak ada harapan lagi. Mungkin memang sudah saatnya.
Dua minggu kepulanganku dari Rumah Sakit, membuatku semakin terbiasa dengan penderitaan ini. Kadang terpikir apa memang semua manusia harus merasakan penderitaan yang sama di akhir hayatnya? Sepertinya tidak semua orang begitu. Ada yang tiba-tiba mati tanpa harus merasakan penderitaan terlebih dulu. Ada yang harus menderita seperti aku ini. Ada yang mati muda, ada juga yang harus menunggu usia senja. Semuanya memang takdir untuk dijalani, kita tidak bisa memilih. Kita hanya pasrah saja.
Aku selalu diajarkan, bahwa apapun yang kita hadapi harus selalu disyukuri. Sekalipun itu suatu penderitaan. Selama ini aku juga pernah melihat ada yang harus mati dalam kesendirian. Setidaknya aku masih memiliki Rohmi, belahan jiwa yang setia sampai saat ini. Setidaknya itu juga yang aku tahu. Aku tidak tahu Rohmi seperti apa diluar sana. Setiap pagi dia meninggalkan aku sendirian di rumah setelah menyuapiku dengan semangkok bubur. Siangnya dia hanya kembali sekitar setengah jam untuk mengirimiku makan siang. Kadang kalau sempat, dia akan menyuapiku nasi dengan soto ayam, rawon, sop buntut, atau apapun yang ia bawa dari warung dekat pasar. Itu semua memang kesukaanku. Tetapi kalau tidak sempat, dia akan segera pamit untuk berangkat bekerja lagi. Kadang kalau merasa lapar aku masih mau makan sendiri. Tetapi kalau perut sudah terasa penuh, hanya perasaan mual dan sebah, aku tidak menyentuh jatah makan siangku itu sampai Rohmi kembali di sore hari. Biasanya dia akan menggerutu berjam-jam gara-gara itu.
“Bagaimana mau sembuh kalau makan saja tidak mau?” kata-kata yang hampir selalu kudengar setiap saat sebelum akhirnya dia memaksaku makan dengan menyuapiku seperti bayi dalam buaian. Aku tersenyum kecut. Sebenarnya aku sudah bosan dengan semua ini. Tapi aku tahu Rohmi mungkin lebih bosan lagi. Aku hanya bisa menuruti kata-katanya selagi aku bisa, sekedar tidak mau membuatnya kecewa. Aku tahu mungkin Rohmi memiliki harapan-harapan yang indah di balik semua ini. Harapan-harapan yang tidak pernah bisa aku penuhi lagi.
Semakin sering aku memperhatikan wajahnya saat dia menyuapiku. Wajahnya yang manis, senyumnya yang ikhlas penuh kesabaran, menyertai ketabahannya menghadapi hidup yang mungkin dia rasakan pahit ini. Sebenarnya dia pantas untuk bahagia bersama yang lain, bukan malah menderita bersamaku. Dia masih muda, pasti banyak lelaki-lelaki perkasa yang ingin membahagiakan dia. Aku tahu mungkin ada yang disembunyikannya dariku tentang apa yang dia dapatkan di luar sana. Aku sebenarnya sering tidak tahan untuk mengutarakannya.
Aku pernah terucap tentang hal itu. Tapi katanya, “Ah, sampeyan ini ngomong apa sih? Kalau mau sembuh jangan mikir yang enggak-enggak dulu lah! Sudah, ya? Nih makan lagi!” sambil menyodorkan sendok berisi nasi ke mukaku. Hanya itu yang pernah kudengar.
Malam semakin larut. Sepertinya aku memang semakin terbiasa dengan ini semua. Penderitaan yang kurasakan bukannya semakin berat tetapi semakin ringan, seiring dengan keikhlasanku menerima semuanya. Aku sudah pasrah. Mungkin sekarang sudah dalam tingkat kepasrahan tertinggi. Aku tidak punya harapan apa-apa lagi selain kebahagiaan Rohmi saja. Wajahnya kini semakin manis saja. Pandanganku padanya semakin jelas, tubuhku semakin terasa ringan, rasa sakitkupun mendadak hilang. Kurasakan tubuhku melayang, semakin tinggi, kulihat ragaku tergolek di sebelah tubuh Rohmi. Aku semakin terangkat ke atas, aku melihat semuanya. Rupanya aku memang harus pergi sekarang.
Selamat tinggal semuanya.
Malam beranjak larut. Mataku terbuka kembali seketika Rohmi merebahkan tubuhnya di sebelahku. Sempat kulihat wajah letihnya yang menyiratkan perasaan pilu. Perempuan itu masih setia menemaniku hingga di usia senja seperti ini. Diapun mulai memejamkan mata. Aku sering memperhatikan raut wajahnya yang belakangan semakin menunjukkan penderitaan. Bukan lantaran merasakan penderitaan yang kualami, tetapi penderitaan yang lain. Entah karena apa. Aku tidak bertanya. Paling-paling dia tidak lagi mau bercerita. Alasannya sudah bisa ditebak: tidak mau menambah penderitaanku.
Perempuan itu tertidur semakin lelap. Wajahnya yang redup seperti rembulan, seakan menahan kepedihan hatinya. Rohmi… andaikan saja aku masih akan sehat seperti hari-hari lalu… niscaya aku akan lebih membahagiakanmu lagi. Kesetiaanmu begitu dalam, saat ini aku tak sanggup membalasnya dengan apapun. Sekarang aku lebih banyak membebaninya dengan sakitku. Tapi aku juga tidak pernah meminta sakit. Dia datang begitu saja tanpa permisi. Dokter bilang aku sudah stadium lanjut. Sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Aku hanya tinggal menunggu waktu dan keajaiban.
Oh, andaikan saja…. Seandainya… semakin banyak andai-andai dalam pikiranku belakangan ini. Salahku juga. Mengapa tidak saat masih sehat dulu aku sering menjaga diri. Belakangan sering muncul penyesalan. Penyesalan yang tidak berarti apa-apa. Penyesalan yang tiada berguna. Baru sekarang merasa kalau kesehatan itu begitu mahal. Sudah berapa juta uang habis buat perawatanku di Rumah Sakit, belum lagi buat ke sana ke mari. Penghasilan pun sudah tidak ada. Apa yang bisa dihasilkan dari si tua renta ini? Aku benar-benar bergantung kepada Rohmi. Hanya dia satu-satunya harta yang aku punya. Pun aku tak mau lagi semakin membebaninya. Lebih baik aku pulang paksa dari Rumah Sakit agar Rohmi bisa merawatku di rumah. Toh sudah tidak ada harapan lagi. Mungkin memang sudah saatnya.
Dua minggu kepulanganku dari Rumah Sakit, membuatku semakin terbiasa dengan penderitaan ini. Kadang terpikir apa memang semua manusia harus merasakan penderitaan yang sama di akhir hayatnya? Sepertinya tidak semua orang begitu. Ada yang tiba-tiba mati tanpa harus merasakan penderitaan terlebih dulu. Ada yang harus menderita seperti aku ini. Ada yang mati muda, ada juga yang harus menunggu usia senja. Semuanya memang takdir untuk dijalani, kita tidak bisa memilih. Kita hanya pasrah saja.
Aku selalu diajarkan, bahwa apapun yang kita hadapi harus selalu disyukuri. Sekalipun itu suatu penderitaan. Selama ini aku juga pernah melihat ada yang harus mati dalam kesendirian. Setidaknya aku masih memiliki Rohmi, belahan jiwa yang setia sampai saat ini. Setidaknya itu juga yang aku tahu. Aku tidak tahu Rohmi seperti apa diluar sana. Setiap pagi dia meninggalkan aku sendirian di rumah setelah menyuapiku dengan semangkok bubur. Siangnya dia hanya kembali sekitar setengah jam untuk mengirimiku makan siang. Kadang kalau sempat, dia akan menyuapiku nasi dengan soto ayam, rawon, sop buntut, atau apapun yang ia bawa dari warung dekat pasar. Itu semua memang kesukaanku. Tetapi kalau tidak sempat, dia akan segera pamit untuk berangkat bekerja lagi. Kadang kalau merasa lapar aku masih mau makan sendiri. Tetapi kalau perut sudah terasa penuh, hanya perasaan mual dan sebah, aku tidak menyentuh jatah makan siangku itu sampai Rohmi kembali di sore hari. Biasanya dia akan menggerutu berjam-jam gara-gara itu.
“Bagaimana mau sembuh kalau makan saja tidak mau?” kata-kata yang hampir selalu kudengar setiap saat sebelum akhirnya dia memaksaku makan dengan menyuapiku seperti bayi dalam buaian. Aku tersenyum kecut. Sebenarnya aku sudah bosan dengan semua ini. Tapi aku tahu Rohmi mungkin lebih bosan lagi. Aku hanya bisa menuruti kata-katanya selagi aku bisa, sekedar tidak mau membuatnya kecewa. Aku tahu mungkin Rohmi memiliki harapan-harapan yang indah di balik semua ini. Harapan-harapan yang tidak pernah bisa aku penuhi lagi.
Semakin sering aku memperhatikan wajahnya saat dia menyuapiku. Wajahnya yang manis, senyumnya yang ikhlas penuh kesabaran, menyertai ketabahannya menghadapi hidup yang mungkin dia rasakan pahit ini. Sebenarnya dia pantas untuk bahagia bersama yang lain, bukan malah menderita bersamaku. Dia masih muda, pasti banyak lelaki-lelaki perkasa yang ingin membahagiakan dia. Aku tahu mungkin ada yang disembunyikannya dariku tentang apa yang dia dapatkan di luar sana. Aku sebenarnya sering tidak tahan untuk mengutarakannya.
Aku pernah terucap tentang hal itu. Tapi katanya, “Ah, sampeyan ini ngomong apa sih? Kalau mau sembuh jangan mikir yang enggak-enggak dulu lah! Sudah, ya? Nih makan lagi!” sambil menyodorkan sendok berisi nasi ke mukaku. Hanya itu yang pernah kudengar.
Malam semakin larut. Sepertinya aku memang semakin terbiasa dengan ini semua. Penderitaan yang kurasakan bukannya semakin berat tetapi semakin ringan, seiring dengan keikhlasanku menerima semuanya. Aku sudah pasrah. Mungkin sekarang sudah dalam tingkat kepasrahan tertinggi. Aku tidak punya harapan apa-apa lagi selain kebahagiaan Rohmi saja. Wajahnya kini semakin manis saja. Pandanganku padanya semakin jelas, tubuhku semakin terasa ringan, rasa sakitkupun mendadak hilang. Kurasakan tubuhku melayang, semakin tinggi, kulihat ragaku tergolek di sebelah tubuh Rohmi. Aku semakin terangkat ke atas, aku melihat semuanya. Rupanya aku memang harus pergi sekarang.
Selamat tinggal semuanya.


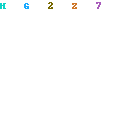








0 komentar:
Posting Komentar