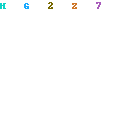Langit masih berselimut mendung, hujan masih deras menikam bagai seribu anak panah di hatinya yang semakin terkoyak. Jadi dia hanya diam membisu di kamarnya yang sepi dan gelap, tanpa lampu. Badai petir dan halilintar masih terkadang menggelegar seirama jeritan hatinya yang tercabik-cabik. Tetes air mata tak lagi mampu ditahannya, meskipun lelaki sejati ini mengaku tidak pernah menangis.
Adalah sang Rama yang tersayat hatinya karena cintanya telah dinodai, membakar ranjangnya sendiri dengan dendam. Ranjang dengan lambang cinta sang Dewi Shinta itu kini telah jadi hangus menjadi serpihan-serpihan abu. Adalah Rahwana yang telah merebut cinta suci itu darinya. Cinta yang dia persembahkan dengan segenap hati dan setulus jiwanya. Cinta dari hatinya yang hanya satu, yang tidak berbelah dan tidak terbuat dari besi.
Dibukanya jendela kamar, dirasakannya hembusan angin menerpa wajahnya yang telah kusut. Rinaian air hujan telah membasahi wajahnya dan berpadu dengan air mata yang terus meleleh. Hanya satu nama yang selalu ia sebut-sebut. Shinta sang kekasih hati telah pergi, berselingkuh dengan pria berada, nun jauh di seberang sana. Hatinya semakin meradang dendam, betapa teganya sang kekasih yang dicintainya selama bertahun-tahun kini pergi begitu saja tanpa alasan.
Matanya lalu tertuju ke laci almari, dimana ia pernah menyimpan sepucuk pistol. Sebatang peluru sudah cukup untuk menyudahi hidupnya yang kini tengah berseklibut dengan keputusasaan. Sayangnya ia tak mampu lagi mengingat dimana ia simpan peluru terakhirnya itu. Yang dia ingat hanyalah sebotol racun serangga yang ia simpan di kamar sebelah. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya ia tidak akan bunuh diri kalau hanya dengan racun serangga itu. Nggak berkelas! Masih lebih keren kalau bunuh diri dengan pistol yang meledak di kepalanya. Disamping itu, rasa dan aromanya tidak enak untuk diminum, bahkan ia harus mengalami sakit perut lebih dulu sebelum akhirnya benar-benar mati. Itupun masih bisa gagal kalau kadar racunnya belum cukup untuk membunuhnya. Hasilnya ia akan malu dengan para tetangga karena gagal bunuh diri.
Dia masih berpikir. Tapi kali ini ia berencana membunuh sang Rahwana keparat itu. Tapi ia tak punya ide bagus untuk melakukannya sekarang. Hatinya yang patah sangat mengganggu ide-ide cemerlangnya. Sepertinya ia perlu waktu untuk membangkitkan kembali semangat juangnya dengan perencanaan yang matang dan strategis.
Malam berikutnya ia masih terbengong sepi di kamarnya yang hangus terbakar. Hujan dan badai tak lagi turun. Ia belum juga menemukan titik terang, apa yang harus diperbuatnya. Sebatang arang yang ia temukan diantara serpihan-serpihan ranjang itu diraihnya untuk mulai menggores di sebagian dinding yang masih putih.
Plan A: ia akan mengikhlaskannya. Biarlah Shinta kekasih hatinya itu bahagia di ranjang orang. Hatinya penuh harap kepada Sang Hyang Widhi, agar kebahagiaan selalu dicurahkan kepada kekasih hatinya itu, dimanapun ia berada. Tiba-tiba hilang keinginan meneruskan menulis plan A, lalu diambilnya gitar dan mulai bersenandung lagu sedih. Lagu yang keluar dari hatinya begitu menyayat. Seperti senandung kehancuran yang lainnya. Badai masih berkecamuk dalam hatinya, dan lagu yang dinyanyikannya pun semakin keras menghentak. Seperti musik-musik aliran heavy metal di era 80-90an.
Setelah selesai dengan nyanyiah hati yang ia senandungkan selama kurang lebih 10 menit, iapun letih. Ditaruhnya gitar di sudut ruangan dan iapun lelap tertidur.
Akan tetapi di dalam mimpinya, lagu itu belum berhenti bersenandung. Semakin menghentak dan semakin keras. Bahkan teriakan serigala malam pun tak ada yang sekeras nyanyian itu. Bayang-bayang dalam mimpinya silih berganti datang dan pergi dengan suara-suara yang seolah-olah didengarnya. Sesekali badannya terkejut-kejut selama ia tidur. Bola matanya yang terpejam tampak menggeliat-geliat mencari-cari sesuatu. Nafas tidurnya terengah-engah, bagaikan sedang berperang. Tangan dan kakinya kejang-kejang di saat-saat tertentu. Hingga pada suatu jam tertentu, terbangunlah ia dari tidurnya.
Seolah tidak terima diperlakukan tidak adil, segera dicarinya kembali sebatang arang dan melanjutkan dengan Plan B. Sebab Plan A akan sangat mungkin gagal dia wujudkan.