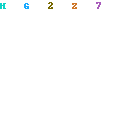“Kedelep…! Kedelep…! Kedelep…!”
“Opo to kuwik?”
“Aku sing ngendhangi, kowe sing nyanyi!”
“Weh … wegah! Aku raisoh nyanyi!”
“Yowis, neknu kowe sing ngendhangi…. Ndang!”
“Kedelep…! Kedelep…! Kedelep…!”
“Wakakakakakak……!”
“Lho, malah ngakak?”
“Lucu!”
“Kendhang kok kedelep-kedelep, apane sing kedelep? Aku kok dadi mbayangke sesuatu sing ora-ora.”
“Yen ngono ganti … icikiwirrr… icikiwirrr…”
“Kaya-kayane penak yen dadi pelawak yo? Uripe mung ngakak thok, bayare akeh!”
“Ah, yo ora mesthi! Urip iku katone wang sinawang. Nyawang leliyan katone enak-kepenak, nanging sing nglakoni yo babak bundhas, wong liya ora ngrasakake. Rumput tetangga nampak lebih hijau dari rumput sendiri. Istri tetangga tampak lebih cantik dari pembantu kita di rumah. Rak yo ngono to, Dul?”
“Halah, omongmu ki lho! Nggedhabrus! Wang-sinawang kok malah nyawangi istri tetangga!”
Sang Malam mengajakku mendekam dalam kamar. Kali ini aku ditemani angan-angan saja, karena internet yang biasanya kusetubuhi kini tengah mati. Biasanya listrik juga mati jam segini, tetapi tumben-tumbennya malam ini begitu gemerlap.
Di kampung ini sudah tak ada lagi bola lampu remang-remang dengan cahaya redup bagaikan lilin. Bola lampu temuan Thomas Alfa Edison itu tidak lagi digunakan di era hemat energi seperti sekarang ini. Digantikan dengan lampu-lampu fluoresen dan bahkan lampu yang terbuat dari semikonduktor canggih yang keren dengan namanya LED (Light Emitting Diode).
Tetapi ada yang selalu sama di kampung ini. Selepas isya, tak ada lagi kehidupan di jalan-jalan. Orang lebih suka mengurung diri di rumah, menghadap berhala-berhala mereka yang disebut televisi. Ya, televisi, benda itu memang dari dulu selalu mengurung orang-orang kampung untuk diam di dalam rumah masing-masing. Seperti tersihir oleh apa yang mereka lihat. Kadang saya bertanya, mengapa mereka begitu terhipnotis oleh berhala-berhala itu. Tetapi mungkin mereka juga sebaliknya bertanya, mengapa aku tak menonton televisi dan malah berlama-lama berduaan dengan ponpin? Kadang senyum-senyum sendiri di depan layar sempit itu, seperti orang gila kehilangan makna. Sama-sama pemilik berhala, hanya saja berbeda bentuk lantaran beda selera saja.
Kali ini mereka seperti nyukur-nyukurin aku yang tersesat sendirian di alam nyata kehilangan dunia maya. Sementara mereka asyik masyuk dengan dunia maya yang lain, berpesta pora dengan tontonan penuh hura-hura dan canda tawa. Aku merasa terasing. Sendiri di dalam kamar, memeluk sang Malam dan membiarkan semua angan-anganku beterbangan ke manapun mereka mau menuju.
Di kampung ini sudah tak ada lagi bola lampu remang-remang dengan cahaya redup bagaikan lilin. Bola lampu temuan Thomas Alfa Edison itu tidak lagi digunakan di era hemat energi seperti sekarang ini. Digantikan dengan lampu-lampu fluoresen dan bahkan lampu yang terbuat dari semikonduktor canggih yang keren dengan namanya LED (Light Emitting Diode).
Tetapi ada yang selalu sama di kampung ini. Selepas isya, tak ada lagi kehidupan di jalan-jalan. Orang lebih suka mengurung diri di rumah, menghadap berhala-berhala mereka yang disebut televisi. Ya, televisi, benda itu memang dari dulu selalu mengurung orang-orang kampung untuk diam di dalam rumah masing-masing. Seperti tersihir oleh apa yang mereka lihat. Kadang saya bertanya, mengapa mereka begitu terhipnotis oleh berhala-berhala itu. Tetapi mungkin mereka juga sebaliknya bertanya, mengapa aku tak menonton televisi dan malah berlama-lama berduaan dengan ponpin? Kadang senyum-senyum sendiri di depan layar sempit itu, seperti orang gila kehilangan makna. Sama-sama pemilik berhala, hanya saja berbeda bentuk lantaran beda selera saja.
Kali ini mereka seperti nyukur-nyukurin aku yang tersesat sendirian di alam nyata kehilangan dunia maya. Sementara mereka asyik masyuk dengan dunia maya yang lain, berpesta pora dengan tontonan penuh hura-hura dan canda tawa. Aku merasa terasing. Sendiri di dalam kamar, memeluk sang Malam dan membiarkan semua angan-anganku beterbangan ke manapun mereka mau menuju.
Saderengipun, mbok manawi lepat kula nyuwun sih pangapunten ingkang tanpa umpami. Awit dumugi mriki kula dereng saged ngleksanani punapa ingkang dipun dhawuhaken dening Kanjeng Begawan. Sinaosa sampun makaping-kaping dipun pengetaken, dipun wucal, saha dipun paringi pitedah maneka warni, kula naming ndableg kemawon.
Kados padatan, mbok manawi Kanjeng Begawan sampun nyumurupi punapa ingkang kawula raosaken sapunika, kula naming nyuwun dipun paringi kasempatan malih ingkang radi longgar. Mbok manawi Gusti ingkang Maha Agung taksih peparing yuswa ingkang panjang, kula badhe ngleksanakaken punapa ingkang sampun dipun dhawuhaken dhumateng kula rikala semanten.
Kula sakyektos saged ngrumaosi bilih punapa ingkang kula tindakaken punika sampun nerak paugeran, nalisir saking margi kaleresan. Babagan punika ugi ingkang ndadosaken pusaka Nyai Sekar Pararaton ingkang awujud kaca benggala nalika semanten uwal saking tangan kula, saha sirna tanpa tetilas. Salajengipun, anggen kula saged pinunjul ing apapak nalika rumiyin, naming dados cariyos ing wekdal sapunika, prasasat mboten wonten nyatanipun.
Sanalika kula dados tiyang ingkang ina, saina-inanipun. Kados mboten pantes nggadhahi kuwaos-kuwaos saha punapa kemawon ingkang sampun dados peparingipun Kanjeng Begawan ingkang tansah kula puji. Punapa malih piandel-piandel ingkang saged nyaranani labuh labet kula dhumateng bangsa lan negari punika kadosdene sampun mboten saged dipun ginakaken malih.
Kados padatan, mbok manawi Kanjeng Begawan sampun nyumurupi punapa ingkang kawula raosaken sapunika, kula naming nyuwun dipun paringi kasempatan malih ingkang radi longgar. Mbok manawi Gusti ingkang Maha Agung taksih peparing yuswa ingkang panjang, kula badhe ngleksanakaken punapa ingkang sampun dipun dhawuhaken dhumateng kula rikala semanten.
Kula sakyektos saged ngrumaosi bilih punapa ingkang kula tindakaken punika sampun nerak paugeran, nalisir saking margi kaleresan. Babagan punika ugi ingkang ndadosaken pusaka Nyai Sekar Pararaton ingkang awujud kaca benggala nalika semanten uwal saking tangan kula, saha sirna tanpa tetilas. Salajengipun, anggen kula saged pinunjul ing apapak nalika rumiyin, naming dados cariyos ing wekdal sapunika, prasasat mboten wonten nyatanipun.
Sanalika kula dados tiyang ingkang ina, saina-inanipun. Kados mboten pantes nggadhahi kuwaos-kuwaos saha punapa kemawon ingkang sampun dados peparingipun Kanjeng Begawan ingkang tansah kula puji. Punapa malih piandel-piandel ingkang saged nyaranani labuh labet kula dhumateng bangsa lan negari punika kadosdene sampun mboten saged dipun ginakaken malih.
Hanya ada angin bertiup
Perlahan menguntit waktu
Walau langit makin redup
Menutup hari mengganti baru
Senja kelana masih gemuruh
Mendekap kata dibalik kata
Berderai di sepanjang jauh
Terlintas berkeping dan sirna
Menelusup hidup membara cinta
Rintihan yang menggelegar
Mendamba seutas makna
Mengekang harapan sebentar
Keanggunan kian terkesan
Melantik kebiruan rindu
Lelah menyebar angan
Namun waktu terus berderu
Perlahan menguntit waktu
Walau langit makin redup
Menutup hari mengganti baru
Senja kelana masih gemuruh
Mendekap kata dibalik kata
Berderai di sepanjang jauh
Terlintas berkeping dan sirna
Menelusup hidup membara cinta
Rintihan yang menggelegar
Mendamba seutas makna
Mengekang harapan sebentar
Keanggunan kian terkesan
Melantik kebiruan rindu
Lelah menyebar angan
Namun waktu terus berderu
Waktu terus berubah, tahun berganti, hidup terus berputar, seperti roda, berjalan terus. Angin pun menerpa, jalanan menanjak, menurun, berliku. Sebagaimana ujian, cobaan, halangan, rintangan, tantangan dan godaan. Tak pernah jemu menyapa di sepanjang perjalanan kita.
Saya teringat sebuah kisah tentang seorang nenek yang hampir setiap hari pekerjaannya hanya menangis saja. Hari-harinya dilalui dengan menangis dan terus menangis. Seolah si Nenek tidak pernah tersenyum, hanya wajah kesedihan yang senantiasa ditujukkannya. Ketika ditanya, kenapa kerjanya hanya menangis, maka nenek itupun mulai bercerita. Dia curhat mengenai kondisi anak-anaknya. Dia hanya memiliki dua orang anak, satu laki-laki, satunya lagi perempuan. Mereka semua bekerja sebagai pedagang keliling. Yang laki-laki sebagai penjual bakso, yang perempuan sebagai penjual es.
Di saat musim kemarau, matahari memancarkan terik yang dahsyat panasnya. Udara pun terasa panas dan kering. Di saat seperti ini sang Nenek selalu menangisi nasib anak laki-lakinya. Karena dia terlalu mengkhawatirkan dagangan anaknya yang berupa bakso, pasti tidak akan laku di kondisi cuaca seperti itu. Sebaliknya di saat musim hujan, ketika hari-hari selalu diliputi hujan terus menerus sampai ada kejadian banjir di mana-mana, sang nenek menangisi nasib putrinya yang berjualan es. Tidak akan ada orang yang membeli es dalam kondisi alam seperti itu. Lalu kapan sang nenek punya waktu untuk tidak menangis?
Saya teringat sebuah kisah tentang seorang nenek yang hampir setiap hari pekerjaannya hanya menangis saja. Hari-harinya dilalui dengan menangis dan terus menangis. Seolah si Nenek tidak pernah tersenyum, hanya wajah kesedihan yang senantiasa ditujukkannya. Ketika ditanya, kenapa kerjanya hanya menangis, maka nenek itupun mulai bercerita. Dia curhat mengenai kondisi anak-anaknya. Dia hanya memiliki dua orang anak, satu laki-laki, satunya lagi perempuan. Mereka semua bekerja sebagai pedagang keliling. Yang laki-laki sebagai penjual bakso, yang perempuan sebagai penjual es.
Di saat musim kemarau, matahari memancarkan terik yang dahsyat panasnya. Udara pun terasa panas dan kering. Di saat seperti ini sang Nenek selalu menangisi nasib anak laki-lakinya. Karena dia terlalu mengkhawatirkan dagangan anaknya yang berupa bakso, pasti tidak akan laku di kondisi cuaca seperti itu. Sebaliknya di saat musim hujan, ketika hari-hari selalu diliputi hujan terus menerus sampai ada kejadian banjir di mana-mana, sang nenek menangisi nasib putrinya yang berjualan es. Tidak akan ada orang yang membeli es dalam kondisi alam seperti itu. Lalu kapan sang nenek punya waktu untuk tidak menangis?
Langganan:
Postingan (Atom)