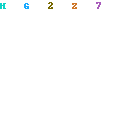Akhirnya sang Jiwa itu terdampar semalaman di sebongkah benua yang pernah memberinya riwayat indah. Tertidur lelap, tanpa mimpi, melewatkan malam yang sepi tanpa cinta. Masih ada segumpal rindu yang tersisa, walau sebagian telah dia lelehkan bersama sang Sandaran Hati di dalam setangkup tirai biru dan sebatang pohon.
Pagi menjelang, membuka jendela kamar dan menatap surga hijau bagaikan dadahanan di hutan. Cengkerama burung-burung pagi beradu dengan nyanyian merdu televisi dan deru mesin jalanan. Langkah kakipun mengajak untuk memijaki jejak semalam dan mengendus-endus dan memilah sejuta aroma. Embun pagipun terheran-heran seakan bertanya, sedang mencari apa disini. Lalu memalingkan pandang pada bunga-bunga trotoar yang berwarna ungu, menari-nari dalam tiupan angin pagi.
Waktu terus merangkak, berderak, melata bagai moluska. Sang Jiwapun menjelajahi ritual pagi, dari kamar mandi hingga ruang makan sebelum akhirnya kembali ke surga: segumpal awan dan ranjang penantian.
Menunggu itu laksana membeku dalam dingin. Tapi sang Jiwa kembali menyematkan keyakinan bahwa merpati yang dinanti tak akan ingkari janji dan sang Sandaran Hati akan indah tepat pada waktunya. Namun keresahan akhirnya memaksanya untuk menunggu di dasar samudra, dimana cintanya pernah disatukan dalam pelukan dan kecupan untuk pertama kalinya.
Pagi menjelang, membuka jendela kamar dan menatap surga hijau bagaikan dadahanan di hutan. Cengkerama burung-burung pagi beradu dengan nyanyian merdu televisi dan deru mesin jalanan. Langkah kakipun mengajak untuk memijaki jejak semalam dan mengendus-endus dan memilah sejuta aroma. Embun pagipun terheran-heran seakan bertanya, sedang mencari apa disini. Lalu memalingkan pandang pada bunga-bunga trotoar yang berwarna ungu, menari-nari dalam tiupan angin pagi.
Waktu terus merangkak, berderak, melata bagai moluska. Sang Jiwapun menjelajahi ritual pagi, dari kamar mandi hingga ruang makan sebelum akhirnya kembali ke surga: segumpal awan dan ranjang penantian.
Menunggu itu laksana membeku dalam dingin. Tapi sang Jiwa kembali menyematkan keyakinan bahwa merpati yang dinanti tak akan ingkari janji dan sang Sandaran Hati akan indah tepat pada waktunya. Namun keresahan akhirnya memaksanya untuk menunggu di dasar samudra, dimana cintanya pernah disatukan dalam pelukan dan kecupan untuk pertama kalinya.